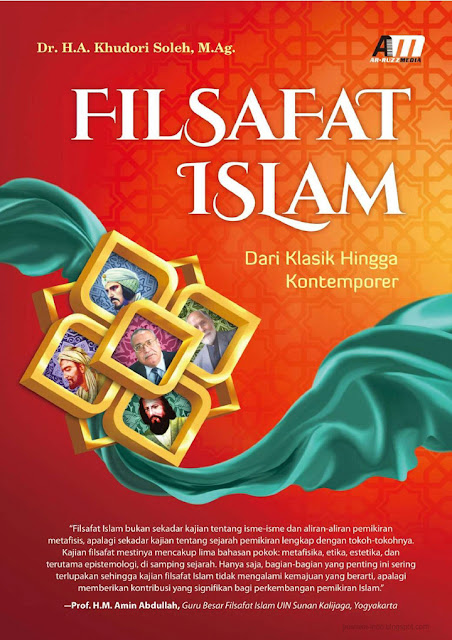Untuk meneruskan buku "Dunia Sophie" yang sudah selesai dibaca di Challenge 22 Hari Baca Buku @22haribacabuku
saya akan meneruskan membaca dua buku Filsafat yaitu buku "FILSAFAT
ISLAM: Dari Klasik Hingga Kontemporer" karya Dr. H. A. Khudori Soleh
M.Ag. untuk memahami lebih dalam mengenai Filsafat dalam Islam setelah
sebelumnya di Dunia Sophie pemikiran Eropa Barat lah yang menjadi acuan
dan buku "FILSAFAT SEBAGAI ILMU KRITIS" karya Franz Magnis-Suseno, S.J.
untuk mengasah lagi dan menghidupkan Filsafat sebagai ilmu kritis yang
merupakan tools penting yang harus kita pelajari.
Saya akan berusaha mengupdate hasil bacaan saya di Instagram dan blog ini. Stay tuned :)
Semoga dilancarkan untuk mendalami lautan ilmu yang begitu luas. Aamiin..
Day 17 #22HBB Vol. 2 (7 April 2023)
5 - 64 – Dzikra Yuhasyra ⚽
📚 FILSAFAT ISLAM: Dari Klasik Hingga Kontemporer - Dr. H. A. Khudori Soleh M.Ag. – hlm. 1-23 / 296
Insight/rangkuman/catatan:
Filsafat
adalah alat. Sebagai alat, ia tidak saja berfungsi mengantarkan kita
untuk masuk memahami kehidupan, tetapi juga menemukan kearifan di balik
kehidupan itu sendiri. Kearifan adalah puncak berfilsafat. Kearifan akan
muncul jika antara aktualitas teori sebagai entitas filsafat dengan
realitas perilaku kita berpadu: membumi dan nyata adanya. Untuk itu,
sudah seyogianya kita berterima kasih kepada para filsuf. Hidup serasa
bermakna berkat amal jariah mereka berupa alat-alat berpikir, metode,
dan pendekatan yang mereka ciptakan dan temukan sehingga menjadikan
kehidupan kita berkualitas. Tanpa filsafat, jangan harap kita dapat
mengetahui dan menjelaskan siapa kita sebenarnya. Namun demikian, buku
ini tidak hanya akan mengajak untuk mengetahui ihwal teknis atau alat
apa yang dipergunakan oleh filsuf-filsuf Muslim untuk berfilsafat,
tetapi juga memperlihatkan bagaimana mereka berpikir dan beberapa
informasi epistemologis yang paling bermanfaat dan memungkinkan untuk
dipahami oleh kita sebagai pembaca. Dari Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd yang
peripetatik, Suhrawardi yang ilmuniasionistik, Mulla Sadra yang teosofi
transenden, Ibnu Arabi dengan wahdat al-wujûd, hingga Al-Kindi dengan
al-falsafah al-ula, semuanya bertujuan mengetahui hakikat realitas
kehidupan dengan menggabungkan segenap sumber pengetahuan secara
integratif: akal, intuisi, dan wahyu.
Benar sebagaimana kritik
Amin Abdullah, Guru Besar Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,
bahwa kajian-kajian fi lsafat Islam yang ada sampai saat ini, di PTAIN
atau PTAIS, bahkan di tingkat Pascasarjana sekalipun, masih lebih banyak
berkutat pada masalah sejarah dan metafisika. Kenyataannya, silabi dan
buku-buku daras Filsafat Islam di Perguruan Tinggi tidak banyak yang
keluar dari dua kajian pokok tersebut.
Bahasannya pun berkisar
masalah sejarah perkembangan filsafat, aliran-aliran filsafat, dan
pemikiran metafisika masing-masing tokoh. Akibatnya, kajian filsafat
Islam menjadi tidak mengalami kemajuan yang berarti, apalagi memberikan
kontribusi yang signifikan bagi perkembangan pemikiran Islam. Padahal,
kajian filsafat sesungguhnya bukan sekadar sejarah dan metafisika,
melainkan juga epistemologi, etika, dan estetika; epistemologi adalah
kajian tentang metodologi dan logika penalaran sehingga filsafat berarti
kajian tentang cara berpikir, yaitu berpikir kritis-analisis dan
sistematis. Artinya, filsafat lebih merupakan kajian tentang proses
berpikir dan bukan sekadar kajian tentang sejarah dan produk pemikiran.
Salah
satu faktor utama kelesuan berpikir dan berijtihad di kalangan umat
Islam sampai saat ini, menurut penulis, adalah disebabkan mereka tidak
mau melihat dan memerhatikan persoalan filsafat (metodologi) ini.
Sebaliknya, seperti ditulis Al-Jabiri (1936–2010 M), sejak pertengahan
abad ke-12 M, pasca serangan Al-Ghazali (1058–1111 M) terhadap filsafat,
hampir semua khazanah intelektual Islam justru selalu menyerang dan
memojokkan filsafat, tanpa memedulikan posisinya sebagai produk,
pendekatan, atau metodologi. Padahal, Al-Ghazali sendiri tidak pernah
menyerang atau menyalahkan filsafat secara keseluruhan, tetapi hanya
pada aspek metafisikanya yang merupakan produk pemikiran, yang dinilai
dapat menyeret pada kekufuran. Namun, filsafat sebagai sebuah proses
penalaran dan metodologi justru tetap dinilai penting dan harus
dikuasai.
Oleh karena itu, dalam
upaya pengembangan dan kajian keilmuan Islam saat ini, kita tidak bisa
berpaling dan meninggalkan filsafat. Tanpa sentuhan filsafat, pemikiran
dan kekuatan spiritual Islam akan sulit menjelaskan jati dirinya dalam
era global. Namun, sekali lagi, apa yang dimaksud filsafat di sini bukan
sekadar uraian sejarah dan metafisikanya yang notabene merupakan produk
pemikiran, melainkan lebih pada sebuah metodologi atau epistemologi.
Karena itulah, Fazlur Rahman (1919–1988 M) menyatakan bahwa filsafat
adalah ruh atau ibu pengetahuan (mother of science) dan metode utama
dalam berpikir, bukan produk pemikiran. Tanpa filsafat, seseorang tidak
akan mampu mengembangkan ilmunya, bahkan tanpa filsafat ia berarti telah
melakukan bunuh diri intelektual.
Berdasarkan alasan itulah,
maka kajian buku ini tidak hanya menyajikan sejarah dan metafisika,
tetapi juga epistemologi, etika, dan estetika. Dalam kajian metafisika,
konsep-konsep metodologi atau pemikiran epistemologi masing-masing tokoh
tetap disampaikan. Subbagian epistemologinya sendiri menjelaskan tiga
model epistemologi yang dikenal dalam Islam: bayânî, irfânî, dan
burhânî. Ketiga model tersebut, dalam sejarahnya, telah menunjukkan
keberhasilannya masing-masing. Nalar bayânî telah membesarkan disiplin
fiqh (yurisprudensi) dan teologi (‘ilm al-kalâm), irfânî telah
menghasilkan teori-teori besar dalam sufisme di samping kelebihannya
dalam wilayah praktis kehidupan, dan burhânî telah mengantarkan filsafat
Islam dalam puncak pencapaiannya. Namun, hal itu bukan berarti tanpa
kelemahan.
Berdasarkan hal itu,
maka masing-masing bentuk epistemologi tersebut berarti tidak memadai
digunakan secara mandiri untuk pengembangan keilmuan Islam, tetapi harus
digunakan secara bersama-sama dan berkaitan. Maksudnya, ketiganya harus
diikat dalam jalinan kerja sama sirkuler untuk saling mendukung,
mengisi, mengkritik, dan memperbaiki kekurangan yang melekat pada
masing-masing. Meski demikian, ketiga-tiganya sekaligus rasanya juga
belum cukup untuk memecahkan persoalan-persoalan keagamaan kontemporer
yang sangat kompleks sehingga perlu ditambah dengan epistemologi tajrîbî
, yaitu bentuk penalaran yang mengandalkan pada eksperimen dan
pengamatan objek fisik secara langsung.
Meski demikian, jalinan
keempat bentuk epistemologi di atas tidak dapat berjalan begitu saja,
tetapi tetap harus didukung oleh disiplin ilmu-ilmu sosial modern,
seperti hermeneutika, sosiologi, antropologi, kebudayaan, dan sejarah
sehingga produk yang dihasilkannya menjadi aktual dan utuh. Karena itu
pula, jalinan epistemologi tersebut juga tidak boleh bersifat final,
eksklusif, dan hegemonik, tetapi harus senantiasa terbuka dan inklusif.
Sebab, finalitas dan eksklusivitas hanya akan mengantarkan pada jalan
buntu dan tidak memberikan kesempatan bagi munculnya
kemungkinan-kemungki nan baru yang mungkin lebih baik dalam menjawab
problem-problem keagamaan dan kemanusiaan kontemporer. Di samping itu,
finalitas dan eksklusivitas berarti menghilangkan kenyataan bahwa
keragaman adalah keniscayaan dan keberagamaan adalah proses panjang
menuju kematangan (on going process), bukan hal instan yang “sekali
jadi”.
@salmanreadingcorner @fimbandung @fimtangerangraya @22haribacabuku
Day 18 #22HBB Vol. 2 (8 April 2023)
5 - 64 – Dzikra Yuhasyra ⚽
📚 FILSAFAT ISLAM: Dari Klasik Hingga Kontemporer - Dr. H. A. Khudori Soleh M.Ag. – hlm. 24-52 / 296
Insight/rangkuman/catatan:
SUMBER-SUMBER PEMIKIRAN RASIONAL-FILOSOFIS DALAM ISLAM
Dapat
disampaikan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pemikiran
rasional-filosofis Islam tidak merupakan jiplakan atau plagiasi dari
filsafat Yunani sebagaimana yang dituduhkan sebagian kalangan, meski
diakui bahwa filsafat Yunani telah memberikan kontribusi sangat besar
bagi perkembangan pemikiran filsafat Islam sesudahnya. Sebab, kenyataan
yang ada menunjukkan bahwa pemikiran rasional dalam hukum (fiqh) dan
teologi Islam Muktazilah telah lebih dahulu mapan sebelum datangnya
filsafat Yunani lewat terjemahan. Pemikiran rasional Islam inilah bahkan
yang telah berjasa memberikan ruang bagi diterimanya filsafat Yunani.
Kedua,
sistem pemikiran rasional Islam tersebut lahir atau muncul dari
analisis dan perkembangan bahasa Arab (nahw), lewat berbagai mazhab
bahasa yang ada. Berawal dari analisis dan rasionalisasi bahasa ini
kemudian berkembang menjadi rasionalisasi dalam bidang hukum (fiqh) dan
teologi, karena adanya kebutuhan untuk menjelaskan secara
rasional-filosofis atas makna dan maksud teks suci dan menjawab
problem-problem yang muncul saat itu secara rasional.
Ketiga,
pemikiran dan fi lsafat Yunani masuk ke dalam khazanah pemikiran Islam
pertama kali pada masa khalifah Al-Makmun (811–833 M) dari dinasti Bani
Abbas (750–1258 M), lewat proyek terjemahan. Proses terjemahan atas
pemikiran rasional filsafat Yunani ini sendiri dilakukan karena telah
berkembang dan mapannya tradisi berpikir rasional filosofis di kalangan
masyarakat Islam, terutama fiqh dan teologi Muktazilah, di samping untuk
mencari tambahan referensi atau amunisi dalam menghadapi
pemikiran-pemikiran heterodoks yang juga mulai berkembang saat itu.
PERGUMULAN FILSAFAT DENGAN ILMU KEAGAMAAN
Pertama,
pemikiran filsafat Islam sesungguhnya tetap dan terus berkembang sampai
masa modern, bahkan kontemporer ini. Hanya saja, ada perubahan bentuk
dan orientasi filsafat setelah masa Ibn Rusyd (1126–1198 M). Yaitu,
pemikiran filsafat yang awalnya berkembang secara mandiri dan bersifat
rasional, kemudian bersinergi dengan tasawuf, sehingga melahirkan
tasawuf falsafi : sebuah pemikiran yang menggabungkan antara pemikiran
rasional dan intuisi. Selain itu, pemikiran rasional-intuitif ini lebih
banyak berkembang di kalangan sarjana Syiah, bukan Sunni, sehingga apa
yang dimaksud bahwa filsafat Islam telah mati pasca-Ibn Rusyd,
sesungguhnya, hanya terjadi dalam masyarakat Sunni, bukan masyarakat
Islam secara keseluruhan.
Kedua, perkembangan filsafat (Sunni),
jika dihitung sejak masa Al-Kindi (806–875 M), tepatnya penulisan buku
‘Filsafat Pertama’ (al-Falsafah al-Ûla) yang dipersembahkan untuk
khalifah Al-Mu`tashim (833–842 M) dan berakhir pada masa Ibn Rusyd
(1126–1198 M), pemikiran filsafat Islam berarti hanya hidup selama
sekitar 350 tahun; suatu masa yang tidak sebentar. Bahkan, jika
dibanding dengan perjalanan Islam sendiri yang dimulai sejak turunnya
wahyu pertama masa Rasul (611 M) sampai sekarang yang berarti telah
berjalan selama 1400 tahun, filsafat Islam berarti telah memberi
kontribusi selama seperempat kehidupan Islam sendiri, suatu masa waktu
yang jelas tidak sedikit.
Ketiga, grafik
perkembangan pemikiran filsafat dalam Islam ternyata tidak senantiasa
naik dan mulus, tetapi juga mengalami pasang surut; pertama-tama
disambut dengan baik karena diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan
menghadapi pemikiran-pemikiran ‘aneh’, tapi kemudian dicurigai karena
ternyata tidak jarang justru digunakan untuk menyerang ajaran agama
Islam sendiri yang dianggap telah baku, khususnya pada masa Ibn Hanbal.
Setelah itu, filsafat dikembangkan oleh Al-Farabi dan Ibn Sina ,
kemudian jatuh lagi karena serangan Al-Ghazali; bangkit lagi pada masa
Ibn Rusyd tapi akhirnya tidak terdengar suaranya, sampai sekarang,
kecuali dalam mazhab Syi`ah.
Keempat, kecurigaan dan penentangan
yang dilakukan oleh sebagian tokoh Muslim terhadap filsafat, seperti
yang dilakukan Ibn Hanbal, bukan semata-mata disebabkan bahwa ia berasal
dari luar Islam, tetapi lebih didasarkan atas kenyataan bahwa saat itu
gerakan filsafat dinilai mengandung dampak yang berbahaya bagi aqidah
masyarakat. Misalnya, pemikiran Ibn Rawandi (827–911 M) dan Al-Razi
(865–925 M) yang sampai menolak kenabian karena mengikuti filsafat, atau
perilaku oknum tertentu yang meremehkan ajaran agama dengan berdasarkan
atas nama filsafat pada masa Al-Ghazali. Akan tetapi, yang harus juga
dicatat adalah bahwa hal itu bukan berarti menunjukkan bahwa seluruh
filosof dan ajaran filsafat adalah salah. Adalah suatu keputusan yang
tidak arif dan tidak tepat jika kita menjatuhkan putusan hanya karena
adanya beberapa kasus yang tidak signifikan dan melupakan jasa-jasanya
yang besar.
Kelima, serangan
Al-Ghazali terhadap filsafat sesungguhnya lebih ditujukan pada aspek
metafi sikanya dan bukan pada logika atau epistemologinya, sesuatu yang
menjadi inti pemikiran filsafat. Sebab, Al-Ghazali sendiri mengakui
pentingnya logika dan menggunakannya untuk membumikan
gagasan-gagasannya. Artinya, dalam analogi fiqh, Al-Ghazali hanya
mengkritik fiqhnya dan bukan ushûl al-fiqh-nya, menolak produk dan bukan
alat atau metodenya. Berdasarkan hal itu, berarti tidak ada alasan bagi
kita untuk menolak filsafat sebagai sebuah epistemologi atau metode
berpikir meski kita bisa tidak sepakat pada bagian metafisika atau hasil
pemikirannya.
Keenam, perselisihan antara kaum filsafat dan
Al-Ghazali tampak juga disebabkan oleh adanya perbedaan dalam memahami
makna dari sebuah istilah yang digunakan. Sebagaimana dikatakan
Al-Hamadani ,44 setiap kelompok atau aliran pemikiran, seperti teologi,
filsafat, tasawuf, fiqh, dan seterusnya mempunyai istilah-istilah teknis
tersendiri, di mana istilah-istilah yang digunakan tersebut bisa jadi
sama tetapi mempunyai makna yang berbeda sesuai dengan yang dimaksud
oleh si pembicara. Karena itu, seseorang dari golongan tertentu tidak
bisa langsung mengklaim atau memberikan makna tentang sebuah istilah
sebelum meminta penjelasan secara baik kepada si empunya istilah.
Menjatuhkan keputusan terhadap pembicara sebelum meminta penjelasan
tentang apa yang dimaksudkan berarti sama dengan menembak dalam
kegelapan, suatu tindakan yang sangat tidak bijak. Ketegangan antara
filsafat dan ilmu keagamaan, termasuk juga ketegangan antara tasawuf dan
fiqh, mazhab fiqh yang satu dengan yang lain, dan seterusnya, rupanya
disulut oleh persoalan ini, tidak adanya sikap tabayun terlebih dahulu
sebelum diambil keputusan. Serangan Al-Ghazali terhadap filosof karena
istilah “qadim” pada alam adalah bukti nyata akan hal itu.
Ketujuh, para tokoh
filsafat Islam, mulai Al-Kindi sampai Ibn Rusyd, dengan caranya
masing-masing sesungguhnya telah dan selalu berusaha untuk menyelaraskan
antara wahyu dan rasio, antara agama dan filsafat, bukan memisahkannya
sebagaimana yang sering dituduhkan. Karena itu, dugaan, asumsi, atau
bahkan tuduhan bahwa filsafat (Islam) telah mengabaikan atau bahkan
meninggalkan ajaran wahyu, kiranya patut dikaji ulang.
@salmanreadingcorner @fimbandung @fimtangerangraya @22haribacabuku